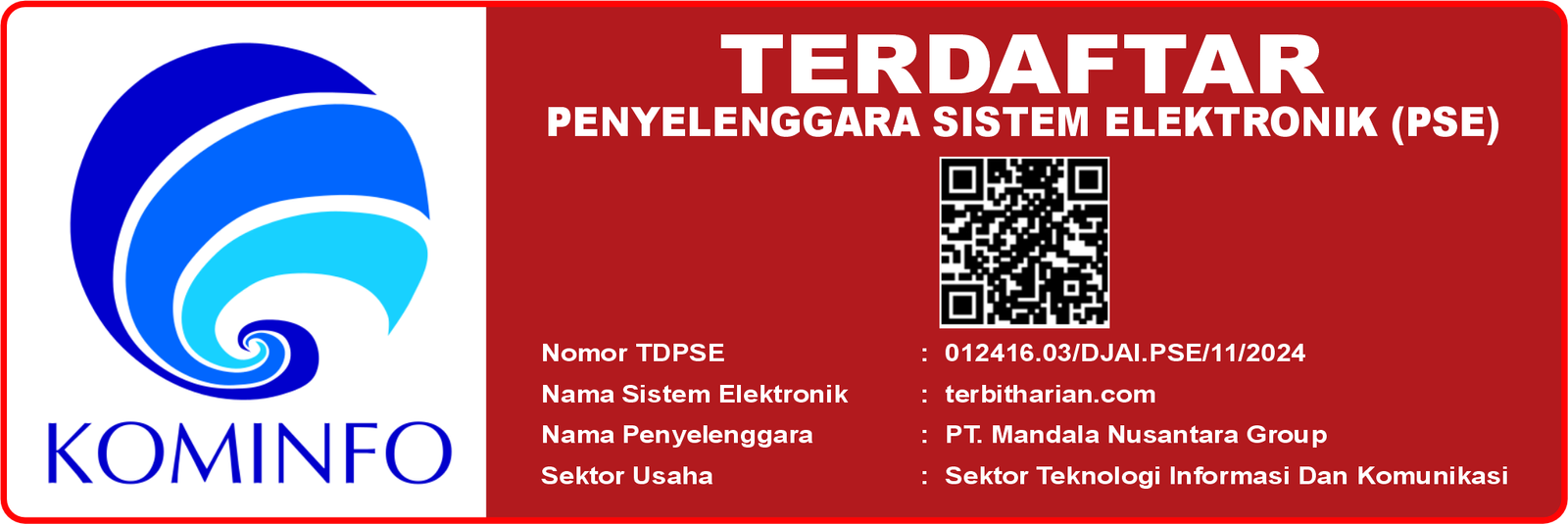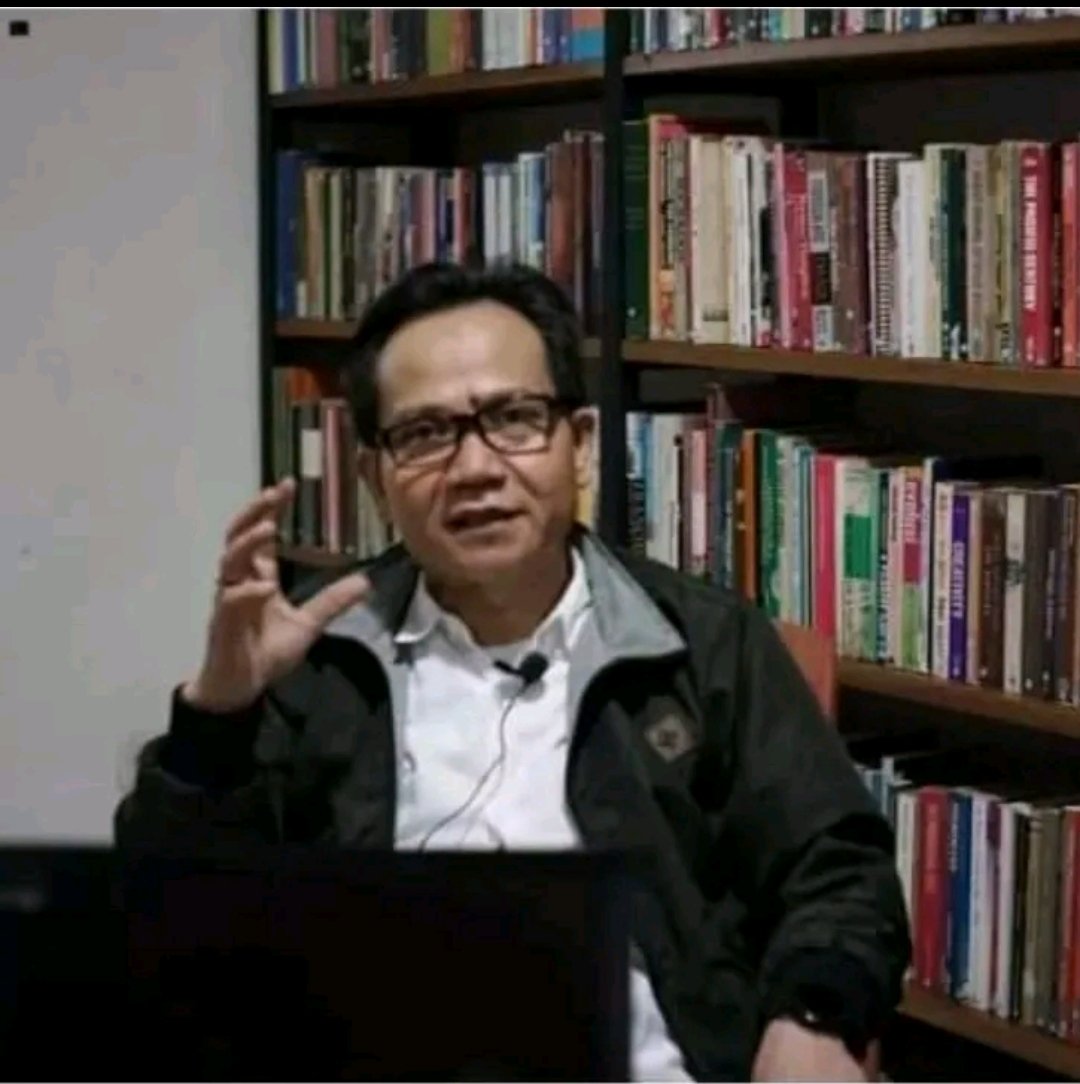Abdul Hakim
Pengajar Studi Perbandingan Politik
STISNU Nusantara Tangerang
Bagian Kedua: Ketimpangan adalah Akar dari Kejahatan Sosial
TERBITHARIAN.COM – Keberhasilan Capital in the Twenty-First Century karya Thomas Piketty tidak dapat semata-mata dijelaskan oleh temuan empirisnya mengenai ketimpangan ekonomi, karena fakta bahwa ketimpangan meningkat tajam sejak akhir 1970-an, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Anglo lainnya, telah lama diketahui oleh para ekonom. Tokoh-tokoh seperti Larry Mishel dari Economic Policy Institute, James K. Galbraith dari University of Texas, Anthony Atkinson di Oxford, hingga Gabriel Palma di Cambridge telah mendokumentasikan tren ini melalui pendekatan berbasis data pendapatan dan upah sejak dekade 1960-an. Bahkan Joseph Stiglitz, seorang peraih Nobel yang populer, dalam The Price of Inequality (2012) telah menyuarakan hal serupa.
Ketimpangan Sebagai Ranah Etika dan Politik
Namun mengapa buku Piketty justru yang meledak di ruang publik? Jawabannya terletak pada faktor kairos – momen yang tepat dalam sejarah sosial dan politik. Jika Capital diterbitkan sebelum krisis keuangan global 2008, besar kemungkinan ia akan tenggelam di antara deretan literatur teknokratis. Namun krisis tersebut menciptakan jeda reflektif dalam narasi kapitalisme global. Masyarakat, terutama di Amerika Serikat, mulai mempertanyakan kredo lama tentang meritokrasi dan kebebasan pasar. Ketika rumah-rumah mereka terancam disita dan sistem keuangan diselamatkan oleh dana publik, retorika tentang ‘politik iri hati’ terhadap orang kaya tidak lagi relevan. Ketimpangan tidak lagi dilihat sebagai konsekuensi alamiah dari kebebasan ekonomi, melainkan sebagai ancaman terhadap keberlanjutan demokrasi dan keadilan sosial.
Ini adalah momen di mana diskursus ketimpangan beralih dari domain ekonomi teknis ke ranah etika dan politik moral. Presiden Obama menyebut ketimpangan sebagai ‘tantangan penentu zaman kita,’ dan Paus Fransiskus menegaskan bahwa ‘ketimpangan adalah akar dari kejahatan sosial.’ Bahkan Alan Greenspan, seorang libertarian konservatif sekaligus pengagum Ayn Rand, menyebut ketimpangan sebagai ‘tren paling berbahaya’ bagi Amerika. Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat global tengah bergeser dari paradigma Homo Economicus – manusia sebagai aktor rasional pencari untung – ke arah paradigma yang lebih reflektif terhadap relasi kuasa, distribusi sumber daya, dan legitimasi sistem ekonomi.
Gerakan sosial seperti Occupy Wall Street, yang mengusung slogan ‘We are the 99%’, merepresentasikan artikulasi politik dari kesadaran kolektif tersebut. Ini bukan lagi sekadar soal ketimpangan sebagai angka statistik, tetapi tentang struktur relasi sosial yang timpang dan menindas. Dalam konteks ini, buku Piketty hadir tidak hanya sebagai karya ekonomi, melainkan sebagai narasi besar yang mengaitkan data dengan argumen historis dan imajinasi moral mengenai masa depan kapitalisme. Dengan demikian, kesuksesan buku ini mencerminkan tidak hanya kejernihan analisis, tetapi juga kemampuannya menangkap zeitgeist—roh zaman—yang merindukan keadilan distribusi dalam dunia yang semakin terpolarisasi.
Respons kalangan super-kaya terhadap narasi ketimpangan yang dibawa Piketty dan didukung oleh berbagai tokoh publik menunjukkan betapa kuatnya resistensi elite terhadap kritik moral dan struktural atas posisi mereka dalam masyarakat. Para miliarder yang selama ini menempatkan diri sebagai ‘pencipta lapangan kerja’, ‘inovator demi kemajuan sosial’, dan ‘filantropis pemecah masalah’ merasa tersinggung dan terancam ketika peran mereka dalam mempertahankan sistem yang timpang mulai dipertanyakan.
Figur seperti Stephen Schwarzman, CEO Blackstone, bahkan menyamakan usulan penghapusan celah pajak untuk manajer hedge fund dengan invasi Hitler ke Polandia. Tom Perkins, seorang kapitalis ventura, secara ekstrem membandingkan kritik terhadap kaum kaya dengan penganiayaan terhadap Yahudi oleh Nazi Jerman. Respons semacam ini menunjukkan bukan sekadar paranoia, tetapi semacam narasi defensif yang melindungi tatanan status quo melalui analogi historis yang menyimpang.
Dukungan sebagian publik terhadap kaum kaya, terutama dari basis pemilih konservatif dan gerakan Tea Party, memperlihatkan bagaimana ideologi libertarian–dengan tokoh sentral seperti Friedrich von Hayek – terus hidup dan bahkan mengalami kebangkitan. Karya Hayek, The Road to Serfdom, yang kembali laris di masa pemerintahan Obama, memperingatkan bahwa setiap intervensi negara demi kesetaraan akan berujung pada otoritarianisme. Dalam kerangka Hayekian ini, redistribusi dianggap sebagai jalan menuju perbudakan modern. Narasi ini begitu kuat hingga mampu menutup ruang diskusi publik mengenai ketimpangan sebagai persoalan keadilan, bukan sekadar efisiensi atau kebebasan.
Kondisi ini menunjukkan bagaimana debat tentang ketimpangan tidak lagi semata soal angka atau data ekonomi, melainkan telah menjadi medan pertarungan ideologis dan moral. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang mendapat apa, tetapi siapa yang berhak mendapat apa, dan atas dasar nilai apa tatanan sosial harus dibangun. Dalam konteks ini, Piketty dan kritiknya terhadap akumulasi kekayaan turun-temurun menjadi ancaman eksistensial bagi elite, karena ia menggugat fondasi moral yang selama ini membenarkan kekuasaan mereka atas ekonomi, politik, dan narasi kebaikan publik.
Mengukuhkan Kegelisahan Kelas Menengah
Kesuksesan Capital in the Twenty-First Century karya Thomas Piketty tak lepas dari kemampuannya merefleksikan dan melegitimasi keresahan kolektif masyarakat Barat pasca-krisis finansial 2008. Berbicara dari dalam sistem dengan metodologi ilmiah dan data historis yang luas, Piketty tidak tampil sebagai radikal, melainkan sebagai “psikoterapis intelektual” yang menamai dan menormalisasi kecemasan sosial akibat ketimpangan. Keresahan ini bukan delusi, tetapi respons rasional terhadap struktur ekonomi global yang semakin timpang—sebagaimana tercermin dalam laporan Global Risks 2012 dan jajak pendapat Gallup yang menunjukkan menurunnya kepercayaan publik terhadap globalisasi dan pemerintah.
Gejala krisis ini termanifestasi dalam munculnya precariat, kelas pekerja yang hidup tanpa kepastian kerja dan sosial, sementara elite ekonomi justru semakin mapan. Di tengah narasi pasar bebas yang mulai runtuh, logika moral tergeser oleh kalkulasi nilai tukar manusia dalam pasar kerja. Di Jerman, buruh disamakan dengan komoditas babi—simbol ekstrem dari banalitas moral kapitalisme yang memutus hubungan antara ekonomi dan martabat manusia.
Kekecewaan publik terhadap sistem ekonomi global menjelma menjadi kemarahan terbuka terhadap elite, terutama di negara demokrasi liberal seperti Amerika Serikat, di mana 93% kenaikan pendapatan nasional antara 2009–2012 dinikmati oleh 1% populasi teratas. Ketimpangan ekstrem ini memicu pertanyaan filosofis tentang legitimasi moral kapitalisme, sebagaimana diajukan oleh Nancy Fraser dan Axel Honneth: bagaimana sistem bisa bertahan jika gagal memenuhi prinsip keadilan distributif dan pengakuan martabat manusia?
Piketty menyebut paradoks ini sebagai kenyataan yang tak bisa lagi disamarkan oleh mitos meritokrasi. Kemarahan dan kecemasan masyarakat kemudian terhubung dengan berbagai isu lain—mulai dari imigrasi, layanan publik yang runtuh, hingga ketegangan geopolitik—menciptakan atmosfer krisis multidimensi yang menggerus kepercayaan pada tatanan lama. Tahun 2014 menjadi simbol dari situasi ini: setiap hari seperti membawa kabar buruk baru, menggambarkan dunia yang semakin muram dan menyesakkan.
Dalam konteks keresahan global terhadap ketimpangan, Capital in the Twenty-First Century karya Thomas Piketty tampil layaknya novel distopia, menyerupai Nineteen Eighty-Four atau Brave New World, dengan memperingatkan bahaya munculnya tatanan neo-feodal ketika kekayaan terkonsentrasi secara ekstrem dan diwariskan lintas generasi, menciptakan kasta ekonomi baru yang terisolasi dari masyarakat luas. Namun, alih-alih berakhir dalam keputusasaan, Piketty menawarkan harapan: bahwa konsentrasi kekayaan bukan takdir sejarah yang tak tergoyahkan.
Dengan pilihan politik yang berani dan kebijakan redistributif progresif, arah sejarah masih bisa diubah tanpa menunggu bencana besar. Ia menegaskan bahwa masa depan tetap terbuka bagi intervensi rasional dan etis—masa lalu tak harus menelan masa depan jika kita berani menata ulang struktur ekonomi dengan lebih adil.
Di sini, Piketty membawa kita untuk merenungkan sebuah dilema filosofis yang telah lama ada dalam pemikiran politik dan ekonomi: apakah kita menerima ketidaksetaraan sebagai hasil alamiah dari sistem kapitalis yang kita pilih, atau apakah kita berani menantang norma-norma tersebut dan membentuk kembali struktur sosial kita dengan lebih adil? Ini bukan hanya soal distribusi kekayaan, melainkan juga soal etika dasar dalam hubungan sosial kita. Piketty, melalui pendekatannya yang berbasis data, mengajak kita untuk berpikir ulang tentang apa yang sebenarnya kita anggap sebagai ‘kemajuan’ dalam masyarakat yang semakin terpecah ini.
Daya tarik Capital in the Twenty-First Century juga terletak pada strategi wacananya yang konvensional dan dapat diterima luas: alih-alih menggunakan istilah “kapitalisme” yang mudah diasosiasikan dengan Marxisme, Piketty memilih “modal”, istilah yang terdengar lebih netral namun tetap mengusik. Popularitas ini, meski tetap memicu reaksi keras—seperti tuduhan “Marxisme yang dicerna kembali” oleh eksekutif Deutsche Bank—menunjukkan betapa sensitifnya topik ketimpangan dalam tatanan ekonomi global.
Piketty memang tidak menawarkan kritik radikal terhadap relasi kekuasaan dalam proses produksi, melainkan tetap berada dalam kerangka neoklasik yang menekankan distribusi ketimbang produksi. Ia menjelaskan ketimpangan melalui produktivitas marginal untuk kelas bawah, sementara untuk elite atas, narasinya cenderung deskriptif tentang akumulasi kekayaan tanpa batas. Kritik seperti dari Thomas Palley menilai pendekatan ini sebagai kosmetika struktural: tampak mengusulkan perubahan, namun tetap mempertahankan teori ekonomi arus utama yang mendasarinya—sebuah strategi gattopardo, di mana “segalanya harus berubah agar semuanya tetap sama.”
Solusi kebijakan yang ditawarkan Piketty, seperti pajak kekayaan global dan sistem perpajakan progresif yang lebih tajam, tetap berada dalam kerangka ekonomi neoklasik yang konvensional, meskipun tingkat redistribusinya jauh melampaui standar kebijakan saat ini.
Dengan memilih jalur reformis ketimbang transformatif—menghindari wacana ‘pre-distribution’ seperti reformasi hukum korporasi atau penguatan serikat pekerja—Piketty secara sadar beroperasi dalam batas aman sistem ekonomi arus utama. Kritiknya terhadap ketimpangan bersifat struktural namun tidak revolusioner, menawarkan koreksi internal tanpa menggugat fondasi kapitalisme itu sendiri. Pendekatan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana redistribusi fiskal cukup untuk mengatasi ketimpangan, dan apakah perubahan kosmetik dalam kebijakan dapat menyentuh akar ketidakadilan yang bersumber dari relasi kekuasaan dalam produksi dan akumulasi modal?
Salah satu hal yang mencolok dalam Capital in the Twenty-First Century adalah hampir tidak adanya perhatian yang diberikan oleh Piketty terhadap pertanyaan mendalam mengenai mengapa ketidaksetaraan itu penting. Piketty lebih banyak berfokus pada mendokumentasikan fakta dan pola distribusi kekayaan, tetapi hampir tidak pernah menyentuh isu tentang kapan ketidaksetaraan sudah menjadi masalah yang tidak dapat diterima atau kapan biaya sosial untuk mengurangi ketidaksetaraan lebih besar daripada manfaat yang dapat diperoleh.
Ini adalah pertanyaan filosofis yang mendasar, tetapi seringkali dihindari dalam diskusi ekonomi arus utama. Alasan mengapa topik ini jarang dibahas, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adalah karena ketidaksetaraan telah menjadi bagian dari struktur yang sangat diterima dalam kapitalisme modern, sehingga menantangnya dianggap mengancam stabilitas sosial dan ekonomi yang ada.
Implikasi Struktural Ketidaksetaraan
Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan lembaga arus utama seperti International Monetary Fund (IMF) mulai mengakui dampak negatif ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pengakuan yang Martin Wolf dari Financial Times sebut sebagai temuan yang “sangat jelas.” Penelitian IMF menunjukkan bahwa ketimpangan yang tinggi bukan hanya persoalan moral atau sosial, tetapi juga hambatan makroekonomi: negara dengan distribusi kekayaan yang timpang cenderung tumbuh lebih lambat dan tidak stabil, sementara negara dengan ketimpangan rendah menikmati pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.
Ketimpangan ekstrem, seperti di negara-negara Anglo-Saxon, menyebabkan ketidakseimbangan struktural antara surplus tabungan di kalangan elite dan lemahnya konsumsi di kelas bawah, yang kemudian memicu gelembung kredit, akumulasi utang, dan krisis finansial. Dalam konteks ini, redistribusi tidak hanya menjadi instrumen keadilan sosial, tetapi juga prasyarat rasional bagi kestabilan dan efektivitas kebijakan ekonomi jangka panjang.
Fenomena ‘balance sheet recession’, seperti yang dialami Jepang pada 1990-an dan negara-negara Barat pasca-2008, memperlihatkan dampak destruktif dari ketimpangan yang berkepanjangan, di mana konsumen dan perusahaan lebih memilih melunasi utang daripada meningkatkan permintaan, sehingga memicu stagnasi ekonomi. Wolfgang Münchau dari Financial Times menggambarkan kondisi ini sebagai jebakan pertumbuhan lambat, inflasi rendah, dan ancaman kebangkrutan serta gejolak politik yang terus-menerus.
Ketimpangan yang ekstrem tidak hanya melumpuhkan dinamika ekonomi, tetapi juga merusak tatanan sosial-politik, memicu ketegangan, dan menggerus legitimasi sistem yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan bukan semata isu teknokratik yang dapat diatasi melalui kebijakan fiskal atau moneter, melainkan persoalan moral dan sosial yang menyentuh inti keadilan dalam masyarakat. Maka, muncul pertanyaan mendasar: mungkinkah kapitalisme bertahan tanpa mengatasi akar ketimpangan strukturalnya, atau justru kita tengah menyaksikan pembusukan dari dalam yang mengancam keberlanjutan sistem itu sendiri?
Dalam The Spirit Level (2009), Wilkinson dan Pickett menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan sangat berkorelasi dengan berbagai persoalan sosial dan kesehatan—dari harapan hidup, angka kematian anak, obesitas, hingga tingkat homisida dan gangguan mental—di lebih dari 20 negara maju dan 50 negara bagian AS. Ketimpangan ini, diukur melalui rasio pendapatan atau koefisien Gini, terbukti berdampak tidak hanya pada kelompok miskin, tetapi pada seluruh masyarakat, dengan beban sosial yang jauh lebih besar di negara-negara yang lebih tidak setara.
Temuan ini diperkuat oleh riset Lawrence Katz yang menunjukkan memburuknya mobilitas pendidikan antar generasi di AS—indikator bahwa ketimpangan ekonomi menjalar ke sektor pendidikan, menghambat peluang peningkatan status sosial, dan memperkuat siklus ketidakadilan struktural. Kedua studi ini menegaskan bahwa ketidaksetaraan bukan hanya persoalan distribusi pendapatan, tetapi juga akar dari krisis sosial yang lebih luas, menciptakan masyarakat yang semakin terfragmentasi dan tidak sehat secara kolektif.
Penemuan tersebut mendorong refleksi mendalam bahwa ketidaksetaraan kontemporer bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga masalah moral dan sosial yang merusak fondasi demokrasi dan keadilan. Ketika jurang ketidaksetaraan melebar, mobilitas sosial yang seharusnya menjadi pilar keadilan justru terhambat, dengan pendidikan yang semakin sulit diakses oleh lapisan bawah. Studi di Eropa dan Amerika mengungkap bias representasional yang menguntungkan kaum kaya, di mana kebijakan publik cenderung memperkuat kepentingan elit melalui pengaturan institusional yang menjaga aliran pendapatan pra-pajak ke atas, sekaligus melemahkan respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat miskin. Jaringan elit yang saling terkait, dari Wall Street hingga universitas besar, mengonsolidasikan kekuasaan dan hak istimewa yang melampaui batas negara, memperkuat ketimpangan dan menggerus demokrasi, sejalan dengan peringatan Louis Brandeis bahwa demokrasi dan konsentrasi kekayaan sulit berdampingan secara berkelanjutan.
Perjanjian perdagangan mega-regional seperti Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) mencerminkan bagaimana korporasi besar, termasuk Siemens dan Veolia, berupaya memperkuat hak istimewa untuk melindungi keuntungan mereka dengan membatasi peran negara dalam mengatur pekerjaan, lingkungan, dan kesehatan publik, sekaligus meningkatkan daya saing bisnis Barat. Di sisi lain, praktik penghindaran pajak dan penyembunyian kekayaan oleh elit kaya yang semakin diterima luas—seperti yang diungkapkan oleh penelitian Zucman—menggarisbawahi bagaimana ketidaksetaraan tidak hanya merusak keadilan ekonomi, tetapi juga melemahkan tatanan sosial dan moral.
Dalam konteks ini, kolaborasi antara negara-negara besar dan elit ekonomi menghasilkan kebijakan yang cenderung menguntungkan pemilik modal dan memperdalam jurang sosial, sekaligus menimbulkan ketegangan antara kekuasaan ekonomi yang tak terkendali dan prinsip demokrasi yang mestinya menjamin pemerintahan yang responsif dan adil bagi seluruh warga.
Meskipun ketidaksetaraan telah menjadi sorotan utama dalam perhatian nasional dan global belakangan ini, kemungkinan untuk menurunkannya secara signifikan tampaknya sangat kecil. Kebijakan dan institusi yang terbentuk pada dekade-dekade pasca-perang yang berhasil menurunkan ketidaksetaraan– seperti tarif pajak tinggi untuk golongan atas, undang-undang yang melindungi kekuatan tawar-menawar serikat pekerja, pembatasan sektor keuangan, kontrol modal, kurs tukar tetap, serta partai politik kiri yang memiliki pandangan progresif–tidak bisa terwujud tanpa adanya ketakutan mendalam dari elit terhadap kemungkinan kerusuhan massal, yang dipicu oleh kenangan akan Depresi dan perang, keberadaan serikat pekerja yang kuat, dan Uni Soviet yang bersenjata nuklir yang tampak sebagai alternatif yang sah untuk kapitalisme.
Ketimpangan ekonomi, sebagaimana tergambar dalam analisis Piketty dan berbagai studi empiris, bukan sekadar fenomena statistik melainkan akar dari kejahatan sosial yang merusak tatanan kolektif. Ketika kesenjangan kekayaan mengkristal menjadi struktur kekuasaan yang timpang, ia melahirkan ketidakadilan sistemik—mulai dari melemahnya mobilitas sosial, terkikisnya kepercayaan publik, hingga menguatnya hegemoni elite yang mempertahankan status quo melalui instrumen politik dan ekonomi.
Narasi meritokrasi pun runtuh di hadapan realitas akumulasi kekayaan turun-temurun yang mengabadikan ketergantungan dan marginalisasi. Dalam konteks ini, ketimpangan bukan lagi sekadar masalah kebijakan, melainkan kegagalan moral yang mengubah relasi sosial menjadi medan pertarungan antara kepentingan segelintir orang dan hak dasar mayoritas—sebuah paradoks kapitalisme yang, tanpa koreksi radikal, hanya akan melanggengkan siklus krisis dan ketidakstabilan.